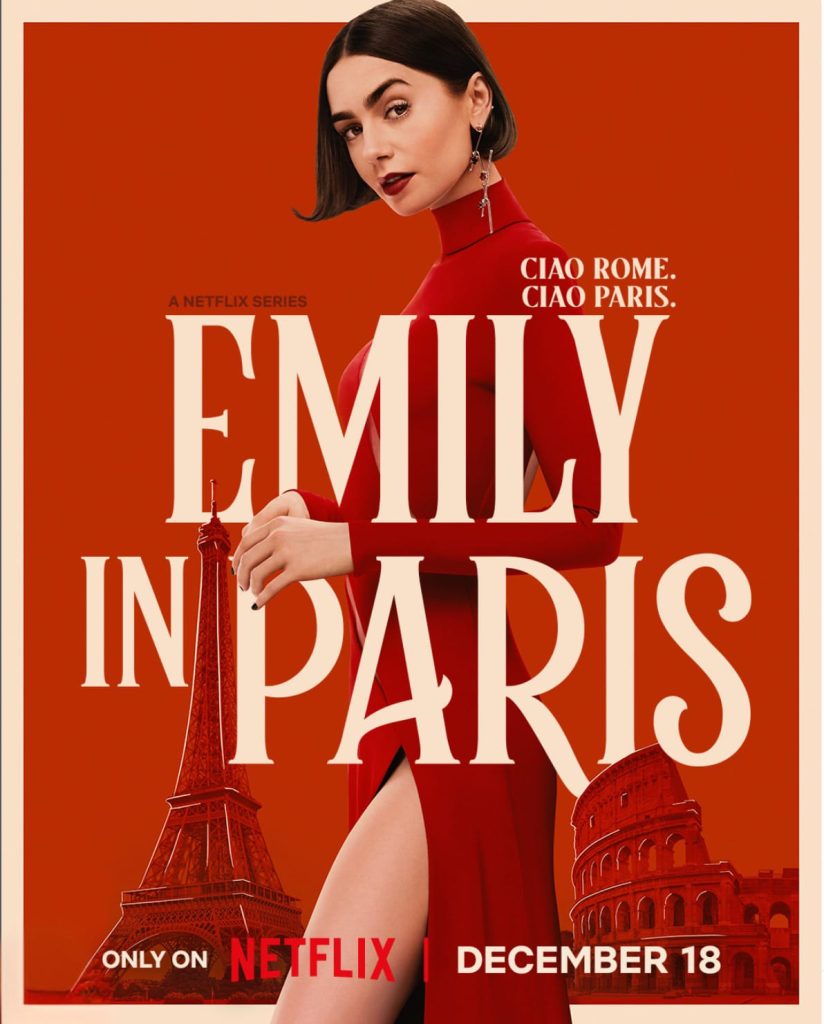“I thought you’re happier when I’m not around..”
Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Alea saat kami melihat-lihat arsip foto lama di Instagram saya. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menghimpit dada. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menarik simpulan seberat itu hanya setelah melihat kotak-kotak gambar kecil di layar ponsel?
Kebetulan Alea belum memiliki akun media sosial. Komentar tadi bermula saat kami ngobrol berdua tentang aneka bentuk potongan rambut. Saya ingin menunjukkan rambut Pixie saya pada tahun 2013. Namun, siapa sangka, selagi saya menggulir layar, matanya yang jeli sibuk mengamati. Ia menemukan bahwa galeri Instagram saya di masa lalu begitu berwarna, jauh sebelum dia hadir dan memenuhi beranda.
Lewat nalarnya yang polos, ia sedang mempertanyakan apakah kehadirannya benar-benar membuat hidup saya lebih berwarna, atau justru sebaliknya? Sebab di mata Alea, foto-foto saya pada rentang 2010 hingga 2014 tampil dengan warna-warna cerah dan kontras yang tajam. Berbeda dengan masa setelah ia lahir, di mana pilihan warna saya berubah menjadi deep & muted colors. Bagi Alea, warna cerah adalah simbol mutlak dari kebahagiaan. Maka saat warna di beranda saya tampak lebih redup, ia menyangka kegembiraan saya pun ikut berkurang.
Mungkin Alea benar. Instagram saya tak lagi seberwarna dulu. Entah mungkin karena kini saya jauh lebih pemilih ketika akan mengunggah konten. Ada idealisme bahwa setiap konten yang saya unggah harus punya cerita yang layak untuk dibagikan. Lagipula, stok foto diri saya sudah tak sebanyak dulu. Sekarang saya lebih sering berada di balik kamera ketimbang di depan lensa, sengaja ingin memberikan ruang bagi cerita-cerita yang lebih baik dibagikan ketimbang disimpan sendiri, terlepas dari apakah ada manfaatnya bagi orang lain atau tidak.
Sambil mencoba meredam haru yang mendadak menyeruak, saya flashback ke era 2010-an, ketika Instagram masih menjadi media sosial yang bersaudara dekat dengan Posterous dan Tumblr. Masa ketika sebagian dari kita mungkin rela menjinjing DSLR ke mana-mana, sengaja berburu objek foto, mengedit dengan saturasi terbaik, dan memastikan setiap inci gambar terlihat sempurna saat diunggah di berbagai platform media sosial.
Dulu, meski hanya bermodal kamera ponsel, saya selalu punya waktu untuk mencari sudut pandang yang pas agar hal-hal sederhana yang saya tangkap bisa terlihat unik. Objeknya pun bisa apa saja, bahkan hal-hal paling acak sekalipun, misalnya setangkai bunga di pinggir jalan, jamur yang tumbuh di sela kursi kayu, arsitektur gedung, mandatory photo memotret bentang alam dari jendela kabin pesawat, hingga cahaya yang membiaskan dasar botol mineral.
Saat itu, saya merasa sebuah gambar baru benar-benar ‘hidup’ jika hadir dengan shadow yang pekat serta warna yang tajam. Keindahan tampilan foto harus kontras agar warnanya bisa langsung dikenali mata.
Namun, ada satu hal yang luput dari ingatan saya adalah Alea tidak pernah melihat proses di balik layar itu. Ia tidak tahu bahwa dulu saya harus ‘memoles’ hasil foto sedemikian rupa agar tampak estetik.
Sementara bagi Alea, setiap gambar yang ia lihat adalah kejujuran yang ia serap utuh. Ia tidak akan mencari saya di balik titik-titik stories Instagram. Ia akan mencari saya di beranda utama dan memastikan bahwa dunia ibunya ini benar-benar masih berwarna ataukah kebahagiaan itu justru memudar sejak ia ada?
Namun, pada kenyataannya, kehadiran Alea memang mengubah cara mata saya menerjemahkan warna. Karena dunia saya menjadi ‘penuh’ sejak kehadirannya. Saya tidak lagi merasa perlu membuktikan kebahagiaan itu lewat polesan warna yang menyala di layar ponsel.
Saya menatap matanya, mencoba mencari kata yang paling sederhana untuk bisa ia simpan dalam ingatannya.
“Alea, rasa sayang orang tua itu tidak bisa diukur dari seberapa berwarnanya postingan mereka di Instagram. Kebahagiaan juga tidak ditentukan oleh seberapa sering kita mengunggah foto keluarga untuk dilihat orang lain.”
Saya mengusap rambutnya, memastikan ia merasa tenang.
“Dulu, kenapa Mama sering posting hal-hal random berwarna terang, Ya, memang begitulah cara dunia bercerita saat itu. Dulu Mama punya banyak waktu untuk memotret objek-objek random dan menulis apa pun di blog, karena itu adalah cara untuk mengisi waktu, jauh sebelum ada Alea. Tapi begitu Alea lahir, kebahagiaan Mama jadi jauh lebih terlihat. Mungkin foto-foto di Instagram Mama tidak lagi seberwarna dulu, tapi itu bukan berarti Mama tidak bahagia. Justru, Mama ingin menampilkan apa adanya keseharian Mama sama Alea. Because you’re the colour itself, Alea.
Air matanya mulai menggenang. Saya melanjutkan pelan.
“Mama sebenarnya lebih suka menulis cerita tentang Alea di Instastory. Di sanalah, Mama mencatat cara berpikir Alea yang unik atau obrolan-obrolan kita yang random. Mama menyimpan semuanya di sana supaya orang-orang tahu betapa istimewanya Alea. Dan kalau kelak kamu cari nama kamu di internet, kamu akan menemukan nama itu tertulis pertama kali di blog Mama di bulan Juli 2014. Selang beberapa hari setelah kamu lahir. Karena sejak hari itu, kamu adalah inti dari semua cerita yang Mama tulis.”
Dalam sekejap, binar matanya redup. Air mata yang ia tahan pun luruh. Ia dekap tubuh saya erat-erat, menyandarkan isak tangisnya dalam pelukan saya. Ada rasa haru yang menjalar saat menyadari bahwa ternyata selama ini, dalam diamnya, ia begitu teliti mengamati setiap keping kebahagiaan saya.
Ketelitian itu sebenarnya selalu ada dalam rutinitas sepulang saya dari kantor. Dengan tulus ia pasti akan bertanya, “How was your day, Mama? Was everything good?” Ia pun punya cara yang sangat manis untuk mengungkapkan isi hati tanpa perlu menunggu alasan. Kapan pun dia mau, dia bisa saja berucap, “I love you…” yang kini saya sadari, itulah caranya menjaga agar ‘warna’ dunia saya baik-baik saja.
Sedikit saja perubahan pada raut wajah saya, ia akan cemas bertanya, “Mama, what’s wrong? Are you okay?” Padahal, mungkin memang begitulah ‘setelan wajah’ saya setelah seharian bergelut dengan lelah, sehingga tidak selalu bisa tampil cerah ceria setiap saat. Namun bagi Alea, sedikit saja mendung bergayut di wajah saya, itu sudah cukup menjadi penanda bahwa dunia saya sedang tidak baik-baik saja. Karena bagi Alea mata adalah indera utama yang ia gunakan untuk menyerap dunia. Di balik tatapan matanya ada pikiran yang sedang bekerja keras mengartikan cinta dengan cara yang sangat luar biasa.
Kesadaran itulah yang membuat saya terdiam dalam sebuah kontemplasi panjang semalam. Apakah selama ini saya terlalu sibuk berdiri di balik lensa, mengabadikan setiap jengkal tumbuh kembangnya hingga lupa untuk masuk ke dalam bingkai yang sama?
Memang ada kebahagiaan tersendiri setiap kali Google Photos memunculkan kembali foto-foto lama. Melihat fisiknya yang berubah, tawanya yang terekam kamera, dan binar matanya yang tak pernah gagal membuat hati saya terasa penuh. Namun, dokumentasi kebersamaan kami bertiga memang kerap kali tidak lengkap, kadang hanya berdua, atau lebih sering hanya dia seorang diri. Saya baru menyadari bahwa Alea tidak hanya butuh direkam. Ia butuh kami ada di dalam frame yang sama dengannya. Ia butuh bukti visual bahwa kami melangkah beriringan.
Jarangnya potret bertiga di beranda ini tak lepas dari kondisi kami yang menjalani pernikahan jarak jauh. Kondisi yang akhirnya menempatkan saya sebagai sosok satu-satunya yang hadir secara fisik dalam kesehariannya. Nun jauh di sana, papanya menjadi pilar yang memastikan kebutuhan kami terpenuhi, agar saya bisa sepenuhnya mendampingi tumbuh kembang Alea dengan optimal.
Di saat-saat inilah saya diajarkan bahwa kebahagiaan kadang tidak tumbuh dalam hiruk-pikuk. Sejujurnya belakangan ini, saya merasa jauh lebih nyaman menumpahkan isi kepala ke dalam bentuk tulisan ketimbang harus berpose di depan kamera. Mungkin kedewasaan perlahan menggeser keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Ada potongan waktu yang terasa terlalu sakral jika harus diganggu oleh bunyi shutter kamera; ada tawa yang cukup disimpan rapat dalam ingatan, tanpa perlu divalidasi oleh jumlah likes di media sosial.
Namun, teguran Alea itu menyadarkan saya untuk mulai mencoba lagi. Saya ingin punya banyak kesempatan untuk mendokumentasikan kebersamaan kami lebih banyak dengan warna-warna cerah. Tentu saja kali ini bukan demi estetika, melainkan agar kelak ia punya jejak visual yang mengingatkannya akan betapa menggembirakannya masa kecil yang dia lalui bersama kami.
Ternyata, kepolosan cara berpikir seorang anak punya caranya sendiri untuk menyentuh hati. Dari Alea, saya belajar tentang arti kehadiran yang utuh, bahwa tugas orang tua bukan sebatas mencukupi raga anak-anaknya saja, melainkan juga merawat persepsi dan saling bertukar isi hati. Menjadi ibu ternyata adalah perjalanan pulang. Dari saya yang dulu sibuk ‘mencari cahaya’ dan spotlight, kini bertumbuh menjadi rumah bagi cahaya itu sendiri.
Kini saya tidak lagi membutuhkan saturasi warna yang tajam untuk merasa benar-benar hidup. Sebab spektrum warna yang paling jujur itu telah saya temukan pada binar mata Alea, pada renyah tawanya yang pecah saat kami berkelakar, pada emosi yang silih berganti mewarnai perjalanan tumbuh kembang kami bertiga, pada rentetan cerita absurd yang mewarnai hari, dan pada hangat yang menyusup di antara pelukan kami setiap waktunya.
Tugas saya sekarang adalah meyakinkan Alea bahwa dialah alasan dunia ini terasa jauh lebih berwarna, meski warna itu tak lagi mampu ditangkap oleh sensor kamera mana pun.
Untuk Alea:
Maafkan Mama ya, jika beranda digital Mama yang sempat kamu lihat tampak lebih redup. Itu karena Mama sedang terlalu sibuk memandangi cahayamu yang begitu benderang di dunia nyata.
-Devieriana-
Gambar ilustrasi: Gemini AI & tangkapan layar Instagram @devieriana